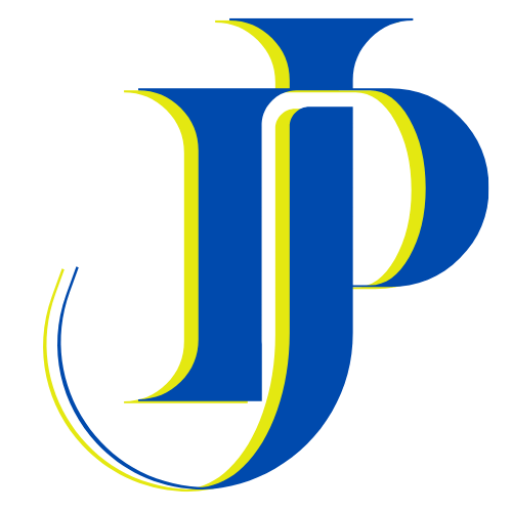Oleh: Laurensius Bagus
Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Ada pemandangan yang sulit diterima akal sehat ketika aparat menjadikan buku sebagai barang bukti dalam proses hukum terhadap para demonstran. Buku, yang seharusnya menjadi sumber pengetahuan dan simbol kebebasan berpikir, diperlakukan seolah-olah ia adalah senjata tajam atau bom molotov. Kejadian ini bukan hanya mencederai logika hukum, tetapi juga memperlihatkan ketakutan negara terhadap gagasan. Demokrasi yang matang seharusnya tidak takut pada kata-kata, tetapi pada kenyataannya, negara justru terkesan panik menghadapi ide yang berbeda.
Demonstrasi adalah ekspresi politik yang sah dalam sistem demokrasi. Jalanan menjadi ruang alternatif bagi rakyat untuk menyampaikan keresahan yang sering kali tidak didengar oleh elite. Namun, alih-alih membuka telinga, negara justru mengedepankan tangan besi. Penangkapan, intimidasi, hingga penyitaan barang-barang pribadi kerap dilakukan demi membungkam suara kritis. Lebih ironis lagi ketika yang disita bukanlah alat kekerasan, melainkan buku. Seakan-akan isi lembaran kertas bisa menimbulkan ancaman yang lebih serius daripada tindakan nyata kekerasan atau korupsi yang merugikan rakyat jauh lebih besar. Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya mental kekuasaan kita: lebih takut pada pemikiran daripada pada kejahatan yang nyata-nyata menghancurkan.
Logika hukum dalam kasus ini terlihat bengkok. Barang bukti seharusnya berhubungan langsung dengan tindak pidana. Jika seseorang dituduh melakukan kekerasan, maka yang disita mestinya adalah batu, senjata tajam, atau benda lain yang digunakan. Tetapi apa hubungannya buku dengan tindak kriminal? Buku hanyalah kumpulan ide. Ia tidak bisa memukul, tidak bisa menembak, dan tidak bisa membakar. Menyamakannya dengan senjata hanya menunjukkan bahwa aparat tidak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat pendemo, sehingga dipaksakanlah gagasan sebagai tindak pidana. Inilah awal dari bahaya kriminalisasi pemikiran: hari ini buku tertentu dianggap berbahaya, besok mungkin diskusi, lusa bahkan tulisan sederhana di media sosial bisa dijadikan dasar pemidanaan.
Praktik penyitaan buku ini jelas memperlihatkan rapuhnya demokrasi kita. Negara yang percaya diri tidak pernah takut pada perbedaan pandangan. Justru keberagaman gagasan adalah penopang utama demokrasi. Tetapi apa yang terjadi hari ini seolah memberi pesan bahwa negara lebih memilih menghindari kritik ketimbang belajar darinya. Demokrasi yang sejati berdiri di atas keberanian mendengar, sementara demokrasi yang rapuh justru terjebak dalam upaya membungkam. Maka tidak mengherankan jika masyarakat mulai meragukan kesungguhan pemerintah dalam menjaga prinsip kebebasan berekspresi.
Dampak dari praktik semacam ini sangat luas. Mahasiswa mulai ragu membaca buku-buku tertentu, penulis khawatir menuliskan pandangan yang terlalu kritis, dan diskusi publik perlahan kehilangan nyawanya. Ketika rasa takut lebih besar daripada keberanian untuk berpikir, bangsa ini sedang menyiapkan generasi yang tunduk, bukan generasi yang berani. Padahal sejarah membuktikan, bangsa yang maju justru dibangun oleh keberanian rakyatnya dalam menguji dan menggugat pemikiran yang mapan. Penyitaan buku, dalam arti yang lebih dalam, sama saja dengan penyitaan masa depan.
Pada akhirnya, tindakan ini hanya memperlihatkan ketidakpercayaan negara terhadap rakyatnya sendiri. Kekuasaan yang kokoh tidak butuh membungkam, karena yakin bahwa ide bisa dihadapi dengan ide lain. Tetapi kekuasaan yang rapuh lebih memilih mengamankan buku ketimbang membuka ruang dialog. Maka penyitaan buku tidak pernah menunjukkan kekuatan negara, justru kebalikannya: ia memperlihatkan kelemahan dan kepanikan. Negara tampak seperti orang yang ketakutan pada bayangannya sendiri.
Solusi dari semua ini sebenarnya sederhana, meski butuh keberanian politik. Pertama, hentikan kebiasaan menjadikan buku sebagai barang bukti. Buku bukan senjata, dan selama isinya hanya berwujud gagasan, ia hanya bisa ditantang dengan gagasan lain, bukan dengan borgol. Kedua, aparat perlu kembali pada logika hukum yang sehat. Hukum harus mengadili perbuatan, bukan pikiran. Ketiga, pemerintah mesti membuka ruang dialog seluas-luasnya, sebab suara rakyat yang protes bukanlah ancaman negara, melainkan bagian dari demokrasi itu sendiri.
Jika penyitaan buku terus dibiarkan, demokrasi kita akan semakin kering. Kita memang masih punya pemilu, tetapi tanpa kebebasan berpikir, demokrasi hanya akan tinggal nama. Buku adalah simbol peradaban. Menyitanya sama saja dengan merendahkan akal sehat bangsa. Negara yang takut pada buku bukanlah negara yang kuat, melainkan negara yang sedang berjalan mundur ke arah kegelapan.