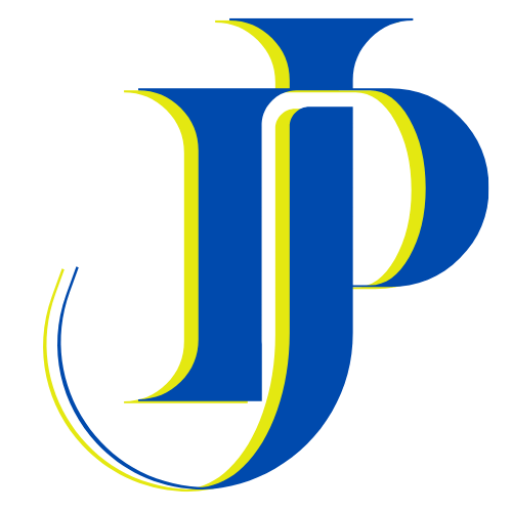*Laurens Ikinia
Di balik hutan purba dan kekayaan mineral yang mendunia, tanah Papua menyimpan sebuah prinsip filosofis yang dalam: masa lalu adalah cermin untuk menatap hari esok. Prinsip ini kini bergema dalam narasi panjang sebuah identitas yang terombang-ambing dan keadilan yang tertunda, menjadikan pulau ini potret nyata dari paradoks pembangunan Indonesia.
Sebelum gemerlap emas dan tembaga menarik perhatian dunia, Papua adalah mahakarya alam yang lestari. Namun, di bawah permukaan tanahnya yang luar biasa subur dan kaya, tersembunyi kisah pilu yang kontras. Kekayaan alam yang melimpah ruah justru berbanding terbalik dengan indikator kesejahteraan manusia yang menghuninya.
Data dan realitas di lapangan menggambarkan sebuah kontradiksi yang suram. Tingkat kemiskinan masih membayangi, kesenjangan akses pendidikan lebar, marginalisasi politik berlangsung halus dan krisis kesehatan menjadi momok di tengah potensi alam yang seolah tak terbatas. Papua, dengan segala kemegahan alamnya, seperti terperangkap dalam bayang-bayang gelapnya sendiri.
“Kami melihat ke belakang untuk memahami ke mana harus melangkah,” begitu kira-kira prinsip yang dipegang dalam kebudayaan setempat. Namun, ketika cermin masa lalu itu memantulkan ketimpangan yang terus berulang, pertanyaannya adalah: masa depan seperti apa yang sedang dibangun untuk tanah surga yang paradoksal ini?
Inilah teka-teki pembangunan yang belum terpecahkan. Ketika hutan-hutan purba menyimpan sejarah, dan perut bumi menyimpan logam mulia, hati dan pikiran masyarakat Papua menantikan janji keadilan dan kesejahteraan yang tak kunjung tuntas. Narasi tentang Papua tidak hanya tentang sumber daya, tetapi lebih tentang manusia, hak, dan masa depan yang setara di bawah naungan merah putih.
Artikel ini berupaya menelisik nasib orang Papua tidak dalam ruang hampa, tetapi melalui lensa perbandingan dengan dua negara tetangga di kawasan Pasifik yang memiliki luka sejarah yang tidak jauh berbeda: Australia dengan masyarakat Aborigin dan Selandia Baru dengan masyarakat Māori.
Penduduk Eropa yang datang ke negeri Kanguru dan negeri Kiwi adalah bangsa pendatang (settler states) yang melakukan kolonisasi, namun kini secara resmi dan institusional bergerak menuju rekonsiliasi dan reparasi, meski jalannya masih berliku. Pertanyaan reflektifnya adalah: Di tengah kompleksitas sejarah dan politik Indonesia, adakah ruang untuk belajar dari langkah-langkah mereka? Bisakah Jakarta menemukan jalan rekonsiliasinya sendiri dengan Papua?
Cermin dari Australia-Aborigin
Hubungan Australia dengan masyarakat Aborigin adalah kisah tentang penjajahan, peminggiran, dan upaya panjang yang belum selesai untuk berdamai. Selama puluhan tahun, kebijakan asimilasi, pencabutan hak, dan generasi yang dicuri (Stolen Generations) meninggalkan trauma mendalam dan berkepanjangan (intergenerational trauma).
Namun, sejak beberapa dekade terakhir, ada pergeseran kebijakan yang menarik untuk diamati, setidaknya dalam empat pilar. Pertama: Dalam Politik – dari ketidakhadiran menuju pengakuan eksistensial. Di Australia, pengakuan formal keberadaan masyarakat Aborigin sebagai warga negara baru terjadi melalui Referendum 1967. Itu adalah titik balik simbolis.
Kini, meski perjuangan untuk Voice to Parliament gagal dalam referendum 2023, diskursus politik Australia telah mengakui istilah First Nations People atau Traditional Custodians dalam pidato resmi, upacara, dan dokumen pemerintah. Ada upaya sistematis, melalui National Indigenous Australians Agency (NIAA).
NIAA dibentuk pada 1 Juli 2019 dengan tugas utamanya adalah untuk mengoordinasikan kebijakan, merancang program, pelaksanaan layanan bagi Masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander. Di tingkat lokal, mekanisme self-determination dalam pengelolaan komunitas telah diuji coba, meski hasilnya beragam.
Perbandingan dengan Papua, Jakarta merespons dengan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2001, yang diperbarui 2021. Otsus adalah instrumen transfer fiskal dan afirmasi politik, seperti syarat gubernur dan wakil gubernur harus putra Asli Papua. Namun, di lapangan, ruang politik itu terasa sempit.
Sentralisasi kebijakan keamanan dari Jakarta, dominasi partai politik nasional di daerah, dan pemekaran wilayah yang sering kali tanpa konsultasi mendalam dengan masyarakat adat membuat esensi penentuan nasib sendiri dalam Otsus mandek. Fondasinya bukan pengakuan historis sebagai mitra, melainkan lebih sebagai kebijakan teknis dari pusat.
Kedua: kebijakan dan pendekatan dalam sektor ekonomi. Australia memiliki Native Title Act 1993, yang mengakui hak kepemilikan tradisional Aborigin atas tanah. Meski proses klaimnya rumit, hukum ini telah mengembalikan jutaan hektar tanah adat.
Program land handback dan pengelolaan bersama kawasan seperti Uluru oleh masyarakat Anangu adalah contohnya. Selain itu, dana abadi dan skema royalty sharing dari sumber daya alam di tanah adat mulai diterapkan, memberikan dasar ekonomi yang lebih mandiri.
Bila dikomparasi dengan Papua, Papua adalah mesin kas terbesar negara Indonesia. Freeport, LNG Tangguh, berbagai jenis proyek perkebunan, perusahaan logging, dan lainnya menjadi pilar ekspor nasional. Namun, struktur ekonominya ekstraktif dan terpusat. Keuntungan mengalir deras ke Jakarta dan kantor pusat korporasi global, sementara masyarakat asli Papua di sekitar tambang sering hidup dalam kontras yang menyakitkan.
Otsus memberikan dana besar, tetapi aliran dana itu tidak mengubah struktur ekonomi yang meminggirkan. Hak ulayat, prinsip dasar ekonomi masyarakat adat, kerap dikalahkan oleh izin usaha pertambangan dan perkebunan skala besar.
Ketiga: kebijakan di sektor Sosial. Australia secara resmi mengakui adanya kesenjangan historis yang luar biasa antara masyarakat Aborigin dan non-Aborigin. Sejak 2008, pemerintah federal meluncurkan Closing the Gap Strategy, sebuah kerangka kerja dengan target-target terukur dan spesifik-seperti harapan hidup, tingkat kelulusan sekolah dan angka pekerjaan-yang dievaluasi dan dilaporkan setiap tahun kepada parlemen. Pendekatannya mengakui bahwa diperlukan intervensi khusus untuk kelompok yang secara sejarah termarjinalisasi.
Ketika dikomparasikan dengan Papua, pemerintah pusat di Jakarta belum memiliki kebijakan nasional setara “Closing the Gap” yang dirancang khusus untuk konteks Papua. Indikator pembangunan disamaratakan dengan daerah lain, mengabaikan kondisi geografis, sosial, dan sejarah yang unik.
Sistem kesehatan dan pendidikan di Papua berjuang melawan keterbatasan infrastruktur, tenaga medis/guru, dan kurikulum yang tidak kontekstual. Angka kematian ibu dan anak, serta gizi buruk, masih tinggi. Pada saat ini banyak program pusat yang difokuskan ke Tanah Papua, namun orang Papua perlu dijadikan subyek dari pada semua kebijakan dan program.
Keempat: dalam sektor kebudaya, di Australia, pengakuan budaya Aborigin telah melampaui sekadar pertunjukan tarian di bandara atau di upaca-upaca seremonial prakmatis semata. Bahasa-bahasa Aborigin didokumentasikan dan diajarkan, hukum adat (customary law) diakui dalam beberapa yurisdiksi tertentu, dan seni Aborigin menjadi bagian penting dari identitas nasional. Pengakuan terhadap Traditional Custodians menjadi ritual pembuka di setiap acara resmi.
Perbandhingan dengan Papua, keunikan dan keragaman budaya Papua dengan lebih dari 250 bahasa adalah kekayaan tak ternilai. Namun, pengakuannya masih sangat simbolis. Bahasa daerah tidak menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan formal.
Hak norma-norma hidup baik dan hak ulayat, yang merupakan jantung hukum adat, mudah ditabrak oleh narasi akulturasi dari luar Papua dan izin usaha. Seni dan ritual dihormati sebagai “aset pariwisata”, tetapi jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan daerah demi mempertahankan jati diri kepapuaan di bumi Cenderawasih.
Cermin Dari Selandia Baru-Māori
Jika Australia menunjukkan perjalanan menuju pengakuan, Selandia Baru menawarkan model rekonsiliasi yang lebih maju, berlandaskan pada sebuah dokumen historis: Treaty of Waitangi (1840). Secara politik, perjanjian yang menjadi fondasi hidup-Treaty of Waitangi, meski penuh dengan kontroversi penafsiran dan pelanggaran massal di masa lalu, kini diterima sebagai dokumen pendiri negara Selandia Baru yang modern. Ia menjadi dasar hukum untuk hubungan antara Mahkota (Pemerintah) dan Māori (Indigenous tribe in New Zealand).
Berdasarkan perjanjian Waitangi, didirikan Waitangi Tribunal (1975) yang bertugas menilai pengaduan historis dan merekomendasikan penyelesaian. Hasilnya adalah proses reparasi besar-besaran berupa pengembalian tanah (pengambilan tanah kembali yang pernah direbut oleh bangsa penjajah), kompensasi finansial, dan permintaan maaf resmi.
Orang Māori juga memiliki kursi khusus (Māori electorates) di Parlemen sejak 1867, memastikan suara mereka tak terdilusi. Lebih dari pada itu, pada tingkatan yang lebih tinggi, orang Māori diberikan partai politik khusus, yakni: Māori Party dan Kementerian khusus yang berurusan dengan kepentingan Orang Māori yakni: Ministry of Māori people. Sebuah langkah yang boleh dikatakan progresif.
Komparasi politik dengan Papua, tidak ada Treaty atau perjanjian kesepakatan bersama yang menjadi fondasi hubungan pemerintah Indonesia dan Papua. Integrasi Papua ke NKRI ditempuh melalui Act of Free Choice (Pepera) 1969, yang legitimasinya terus diperdebatkan secara internasional dan dianggap pahit oleh banyak orang Papua. Akibatnya, tidak ada dasar bersama yang disepakati untuk membangun hubungan ke depan. Relasi dibangun di atas fondasi yang retak.
Sekalipun Papua diberikan Otonomi Khusus, DNA masalahnya belum tersentuh. Banyak pihak berpandangan bahwa Jakarta terkesan belum siap untuk dialog terbuka tentang sejarah integrasi Papua, sehingga luka itu terus terbuka dan menginfeksi setiap kebijakan baru. Proses ini sakit, mahal, dan panjang, tetapi memberikan landasan moral dan hukum yang jelas.
Secara Ekonomi, penyelesaian melalui Waitangi Tribunal telah mentransfer miliaran dolar Selandia Baru dan aset produktif (perikanan, kehutanan/tanah) kembali ke Masyarakat pribumi. Orang Māori memiliki tiga unit sosial atau satuan sosial, iwi (aliansi/konfederasi), hapu (klen/sub-klen), dan whanau (keluarga inti). Iwi kini menjalankan korporasi tribal yang powerful di bidang ekonomi. Ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi pengembalian sumber daya untuk membangun kedaulatan ekonomi.
Perbandingan dengan Papua, ekonomi Papua masih didominasi oleh ekstraksi sumber daya untuk kepentingan Jakarta dan pihak lain. Tidak ada mekanisme reparasi atau pengembalian aset skala besar kepada/oleh suku-suku asli di Papua. Dana Otsus, lebih menyerupai dana hibah yang tidak mengubah struktur kepemilikan dan kontrol atas sumber daya alam. Keluhan ini penulis dengar dari berbagai pihak di Papua.
Secara Sosial-Budaya, Selandia Baru meluncurkan kebijakan biculturalism dan revitalisasi bahasa Māori secara nasional. Bahasa Māori (te reo Māori) adalah bahasa resmi. Ada saluran televisi Māori (Māori Television), sekolah immersion bahasa Māori (kura kaupapa), dan kurikulum nasional yang memasukkan sejarah dan perspektif Māori. Menariknya lagi, di setiap Universitas besar ada fakultas Māori and Pacific studies. Di dalam fakultas tersebut ada berbagai bidang studi yang roh dan dasar filosofisnya berbasis pada budaya Māori.
Perbandingan dengan Papua, bahasa-bahasa lokal Papua terancam punah. Pendidikan masih didominasi kurikulum nasional yang minim muatan lokal. Tidak ada media televisi nasional yang dikelola oleh dan untuk orang Papua dengan jangkauan luas. Papua yang mengandung dan menyimpan kekayaan kearifan lokal itu, belum memiliki program studi khusus yang mengkaji tentang dan untuk merevitalisasi budaya Papua yang berciri khas Melanesia.
Belajar dari Negeri Kanguru dan Negeri Kiwi untuk Papua
Mempelajari pendekatan Australia dan Selandia Baru terhadap masyarakat adat bukanlah skenario salin-tempel. Konteks Indonesia, khususnya Papua, unik dengan sejarah integrasi dan sensitivitas keamanan nasional yang tinggi. Namun, ketakutan akan disintegrasi sering kali justru mematikan inovasi kebijakan yang diperlukan untuk menyelesaikan akar konflik.
Dari Australia, Jakarta dapat mengambil prinsip pengakuan eksistensial. Langkah pertama adalah mengakui Orang Papua sebagai masyarakat adat dengan hak-hak khusus serta sebagai pemilik sah sejarah dan budaya tanah mereka.
Fondasi dari pengakuan ini harus berupa penguatan hukum (penguatan supremasi UU Otsus) atas hak ulayat untuk meredam konflik agraria. Pembangunan pun perlu berbasis affirmative action yang spesifik, ditujukan untuk menutup kesenjangan historis dalam kesehatan dan pendidikan.
Sementara itu, Selandia Baru menawarkan pelajaran tentang rekonsiliasi berani. Membuka ruang dialog tentang masa lalu yang kelam, meskipun pahit, dianggap sebagai langkah awal penyembuhan. Otonomi Khusus Papua perlu bertransformasi dari sekadar “otonomi dana” menjadi devolusi kewenangan yang nyata, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya.
Kemitraan setara dengan institusi adat seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) menjadi kunci. Selain dari pada itu, perwakilan setiap suku, klen dan aliansi atau konfederasi yang ada dalam unit-unit kebudayaan Papua harus dilibatkan aktif dalam menentukan nasib dalam berbagai sektor.
Berdasarkan refleksi ini, diperlukan lompatan dari retorika menuju aksi konkret. Rekomendasi strategis pertama adalah membangun kerangka rekonsiliasi nasional melalui inisiatif politik tingkat tinggi. Bila memungkinkan, hal ini dapat diwujudkan dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua yang independen disertai pengakuan negara atas pelanggaran HAM masa lalu dan dialog nasional yang setara.
Paradigma Otonomi Khusus sudah didesain ulang menjadi “Otsus Plus”. Namun, transformasi in belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Orang Papua. Transformasi ini mestinya meliputi pemberian hak veto bersyarat bagi pemerintah daerah terhadap investasi besar yang mengancam tanah ulayat, penguatan kewenangan legislatif MRP, serta otonomi penuh atas pendidikan dan budaya. Ekonomi harus dibangun berbasis masyarakat adat dengan legalisasi hak ulayat dan pengelolaan sumber daya yang lebih adil.
Pendekatan keamanan perlu direformasi dan mengutamakan dialog. Secara paralel, diperlukan program nasional terukur, yang fokus pada pembangunan manusia dan infrastruktur dasar. Di tingkat politik nasional, pembuatan kursi tetap bagi perwakilan adat Papua di DPR RI dapat menjamin suara substantif mereka terus terdengar dalam setiap legislasi. Langkah ini sudah dilakukan oleh negara terhadap Aceh.
Sebuah Harapan untuk Tanah Papua
Nasib Orang Papua adalah ujian terbesar bagi kebangsaan Indonesia yang inklusif. Ia tidak bisa lagi hanya dibahas dalam logika keamanan sempit atau dikubur di bawah deretan angka pertumbuhan ekonomi. Papua adalah tentang manusia, tentang identitas yang meminta untuk diakui, tentang sejarah yang menuntut untuk didengarkan, dan tentang masa depan yang ingin ditulis bersama.
Harapan itu tetap ada. Ia terpancar dari semangat anak-anak Papua yang bersekolah, dari dedikasi dokter dan guru lokal, dari suara para pengijil dan pemimpin adat yang menyerukan perdamaian, serta dari segelintir pejabat di Jakarta yang mulai memahami bahwa pendekatan lama perlu dievaluasi kembali.
Yang dibutuhkan sekarang adalah kehendak dan keberanian politik (political will and political courage). Keberanian untuk duduk sebagai saudara, mendengar keluh kesah yang tertahan puluhan tahun, mengakui kesalahan, dan bersama-sama merancang jalan baru. Jika Australia dan Selandia Baru dengan sejarah kolonial mereka bisa memulai perjalanan rekonsiliasi yang belum sempurna itu, maka pemerintah Indonesia pun mampu.
Apalagi sudah ada pengalaman dengan menyelesaikan konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka melalui jalan damai (dialog). Syaratnya satu: menempatkan Orang Papua bukan sebagai masalah yang harus diatasi, tetapi sebagai mitra setara, sebagai saudara sebangsa, dan sebagai subjek penuh dari takdir mereka sendiri di Tanah Air Indonesia. Masa depan Papua yang adil dan damai bukanlah ancaman bagi Indonesia, melainkan puncak dari cita-cita para pendiri bangsa yang sejati. Semoga di era Presiden Bapak Prabowo Subianto harapan ini dapat terwujud.
*Penulis adalah Peneliti di Institute of Pacific Studies dan Dosen Hubungan Internasional UKI, Jakarta