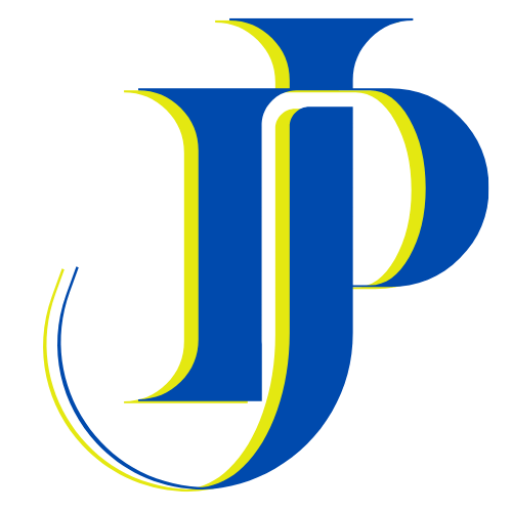Oleh: Laurens Ikinia
Dosen Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia
Dua abad telah berlalu sejak Presiden Amerika Serikat James Monroe menyampaikan pidato kenegaraan yang kelak dikenal sebagai Doktrin Monroe. Deklarasi tahun 1823 itu, yang awalnya dimaksudkan sebagai tameng simbolis bagi negara-negara muda Amerika Latin terhadap ambisi kolonial Eropa, telah menjelma menjadi konsep politik paling tangguh dan paling sering disalahpahami dalam diplomasi hemisferik Barat.
Perjalanannya dari simbol perlindungan menjadi justifikasi intervensi, dan akhirnya menjadi jargon politik yang kabur, bukan sekadar kisah kebijakan luar negeri suatu negara, melainkan cermin evolusi kekuatan, dinamika regional, dan kompleksitas memori kolektif dalam hubungan internasional. Dalam konteks geopolitik kontemporer yang terus berubah, terutama dengan kemunculan dokumen strategis baru seperti National Security Strategy of the United States of America 2025, memahami metamorfosis doktrin ini serta resonansinya yang diperbarui bagi kawasan lain, termasuk Indonesia, menjadi sebuah keharusan yang mendesak.
Pada awal kelahirannya, doktrin tersebut lahir dari ketakutan dan ambisi. Negara-negara di Amerika Latin yang baru merdeka menghadapi ancaman nyata rekolonisasi oleh kekuatan Eropa, sementara Amerika Serikat sendiri cemas dengan ekspansi Rusia di Pasifik Utara. Tawaran Inggris untuk membuat pernyataan bersama ditolak oleh Sekretaris Negara John Quincy Adams, yang melihat peluang bagi Amerika Serikat untuk menegaskan kedaulatannya dan menampilkan diri sebagai kekuatan regional mandiri, bukan sekadar anak buah Inggris.
Doktrin yang dihasilkan kemudian bersifat unilateral dan berani. AS menuntut agar Belahan Bumi Barat bebas dari campur tangan Eropa, dan sebagai gantinya, AS tidak akan mencampuri urusan Eropa. Unsur yang sering terlupakan adalah penekanan doktrin pada bentuk pemerintahan republik, sebuah idealisme yang kontras dengan monarki-monarki Eropa. Ironisnya, pada masa itu, kapasitas militer Amerika Serikat untuk menegakkan doktrin ini hampir tidak ada.
Beberapa pelanggaran oleh kekuatan Eropa terjadi di dekade-dekade berikutnya. Namun, secara politis, doktrin itu disambut positif oleh banyak pemimpin Amerika Latin seperti Simón Bolívar, yang melihatnya sebagai jaminan perlindungan dari kekuatan kolonial. Doktrin Monroe pada fase awalnya lebih merupakan pernyataan aspirasi geopolitik dan solidaritas ideologis daripada manifestasi hegemoni.
Transformasi radikal terjadi pada awal abad ke-20 di bawah Presiden Theodore Roosevelt. Dengan kekuatan ekonomi dan militer AS yang telah membesar, “Corollary Roosevelt” membalik logika awal doktrin. Bukan lagi tentang menjaga Eropa agar tidak masuk, melainkan tentang hak AS untuk masuk secara unilateral ke negara-negara Amerika Latin guna mengoreksi “kesalahan kronis” seperti gagal bayar utang atau kerusuhan dalam negeri, dengan alasan mencegah intervensi Eropa. Dari perisai defensif, doktrin berubah menjadi pedang ofensif yang membenarkan serangkaian intervensi militer AS di Karibia dan Amerika Tengah. Periode ini mengukuhkan citra Doktrin Monroe sebagai alat imperialisme dan paternalisme “Yankee” di benua Amerika.
Pergeseran terjadi lagi menjelang dan pasca Perang Dunia II dengan kebijakan “Tetangga Baik” Franklin D. Roosevelt dan pendirian Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS). Doktrin itu seakan-akan dimultilateralisasi, menekankan kerjasama dan konsultasi. Namun, atmosfer Perang Dingin membangkitkan lagi roh unilateralnya. Meski jarang disebut resmi, logika Doktrin Monroe-yakni hak AS untuk menentukan kondisi politik di “lingkar pengaruhnya”-menjadi dasar bagi berbagai operasi rahasia, kudeta, dan intervensi di Amerika Latin, dari Guatemala hingga Chili, dengan dalih memerangi komunisme internasional. Doktrin itu hidup dalam praktik, jika bukan dalam retorika resmi.
Di abad ke-21, doktrin ini terkesan menghadapi kebingungan mendalam. Ia telah menjadi frasa yang kehilangan makna tunggal, diperebutkan oleh berbagai spektrum politik. Kaum konservatif di AS menggunakannya sebagai seruan untuk ketegasan melawan pengaruh kekuatan ekstra-hemisferik seperti Rusia dan Tiongkok di Amerika Latin, sering kali dengan nada konfrontatif. Kaum liberal mengutuknya sebagai simbol warisan imperialisme yang memalukan. Realitas baru, seperti bangkitnya kekuatan dan agensi negara-negara Amerika Latin sendiri, serta kompleksitas ekonomi global yang saling terhubung, membuat aplikasi doktrin gaya abad ke-19 atau ke-20 tampak janggal dan kontraproduktif. Doktrin Monroe, dalam banyak hal, telah tertinggal oleh zaman, namun hantunya terus menghantui percakapan politik.
Namun, terbitnya National Security Strategy (NSS) 2025 Amerika Serikat memberikan dimensi baru yang konkret dan sangat relevan pada warisan doktrin ini. Dokumen tersebut tidak sekadar mengingatkan pada prinsip-prinsip Monroe, tetapi secara terang-terangan mendeklarasikan kebangkitannya dalam bentuk yang diperbarui dan lebih ofensif: “Trump Corollary to the Monroe Doctrine”. NSS 2025 menyatakan dengan tegas bahwa AS akan menegakkan kembali Doktrin Monroe untuk memulihkan keunggulan Amerika di Belahan Bumi Barat, dengan tujuan melindungi tanah air mereka dan akses ke geografi kunci di seluruh kawasan.
Pernyataan ini lebih dari sekadar retorika. Ia tertanam dalam kerangka strategis yang komprehensif yang berfokus pada “America First”, dengan penekanan kuat pada kedaulatan, ketahanan ekonomi, dan pembagian beban. “Trump Corollary” secara eksplisit bertujuan untuk menyangkal kemampuan pesaing non-Hemispheric-dengan jelas merujuk pada Tiongkok dan Rusia-untuk memposisikan kekuatan, mengendalikan aset strategis, atau memiliki pengaruh yang mengancam di wilayah yang dianggap sebagai “lingkar belakang” strategis AS. Ini merupakan artikulasi yang paling gamblang dalam beberapa dekade terakhir tentang keinginan AS untuk mempertahankan hegemoni regionalnya, tidak lagi melalui multilateralisme yang longgar, tetapi melalui kerjasama selektif yang dikondisikan pada keselarasan kepentingan dan pengucilan pengaruh pihak ketiga.
NSS 2025 menguraikan pendekatan dua cabang untuk Hemisfer Barat: “Enlist and Expand”. “Enlist” berarti merekrut dan memperdalam kemitraan dengan negara-negara yang sudah sejalan untuk mengontrol migrasi, menghentikan aliran narkoba, dan menstabilkan kawasan. “Expand” berarti memperluas jaringan pengaruh AS dengan menjadikan Amerika sebagai “mitra pilihan pertama”, sekaligus secara aktif mencegah kolaborasi negara-negara regional dengan kekuatan eksternal lainnya.
Instrumen yang akan digunakan sangat luas, mulai dari diplomasi komersial dengan tarif dan perjanjian timbal balik, tekanan keuangan dan teknologi, hingga penyesuaian kehadiran militer yang lebih besar untuk tujuan pengawasan dan intervensi langsung terhadap kartel narkoba. Yang lebih signifikan, dokumen tersebut menyerukan integrasi yang lebih dalam antara pemerintah AS dan sektor swasta Amerika untuk mengamankan kontrak, investasi, dan pengembangan aset strategis di kawasan, yang secara efektif mengkombinasikan kekuatan ekonomi dengan tujuan geopolitik. Ini adalah evolusi logis dari Corollary Roosevelt, yang kini dilengkapi dengan alat-alat ekonomi, teknologi, dan keuangan abad ke-21, serta ketegasan yang lebih besar.
Implikasi dan Refleksi Strategis untuk Indonesia
Pelajaran dari siklus hidup Doktrin Monroe, yang kini diperkuat dan diperbarui oleh NSS 2025, sangatlah relevan dan bahkan mendesak bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan besar dengan pengaruh regional yang signifikan, ekonomi yang berkembang, dan lokasi strategis di persimpangan Indo-Pasifik, Indonesia tidak dapat mengabaikan implikasi dari kebangkitan doktrin hemispherik yang lebih ofensif ini. Refleksi ini bukan tentang ketakutan, tetapi tentang kewaspadaan strategis dan pembangunan ketahanan.
Pertama, prinsip kedaulatan dan bahaya konsep “lingkar pengaruh” eksklusif. Doktrin Monroe pada hakikatnya mendefinisikan dan menuntut pengakuan atas back yard strategis AS. NSS 2025 memperkuat ini dengan bahasa yang tidak ambigu. Bagi Indonesia yang berada di jantung Asia Tenggara, ini adalah peringatan yang jelas. Setiap upaya oleh kekuatan besar mana pun-baik AS, Tiongkok, atau lainnya-untuk memperlakukan kawasan ASEAN sebagai “sphere of influence” eksklusifnya, bertentangan dengan kepentingan mendasar Indonesia dan prinsip-prinsip dasar ASEAN.
Komitmen Indonesia terhadap sentralitas ASEAN dan prinsip-prinsip seperti Treaty of Amity and Cooperation (TAC) serta ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality) harus menjadi batu penjuru kebijakan luar negeri. Pengalaman Amerika Latin menunjukkan bahwa sekali logika hegemoni unilateral diterima, ruang manuver negara-negara kecil dan menengah akan menyusut drastis. Indonesia harus secara aktif memastikan bahwa ASEAN tetap menjadi arsitek utama tatanan regionalnya sendiri, bukan menjadi ajang persaingan, atau lebih buruk lagi, subjek dari “corollary” doktrin pihak lain. Ketegasan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan menolak campur tangan asing adalah pertahanan pertama.
Kedua, dinamika kekuatan ekstra-regional dan seni navigasi yang berimbang. NSS 2025 sangat menekankan pengecualian pengaruh “non-Hemispheric” dari Belahan Bumi Barat. Paralelnya di Asia adalah persaingan strategis AS-Tiongkok yang semakin intens, di mana kedua pihak berusaha memperluas jejaring ekonomi, keamanan, dan infrastruktur. Indonesia, dengan kebijakan luar negeri bebas dan aktif, berada dalam posisi yang kompleks.
Pelajaran dari Doktrin Monroe dan NSS 2025 adalah bahwa keterlibatan kekuatan eksternal, meski datang dalam bentuk investasi dan infrastruktur yang menggiurkan, selalu membawa risiko ketergantungan dan penyusutan otonomi strategis. Indonesia harus terus meningkatkan kecanggihan diplomasinya, memastikan bahwa kerja sama dengan pihak manapun tidak mengikat secara eksklusif, tidak menciptakan “debt-traps”, dan tetap sejalan dengan kepentingan nasional serta stabilitas kawasan. Prinsip “free and active” harus diartikulasikan dalam tindakan nyata, seperti keteguhan dalam menjaga kedaulatan di Natuna atau dalam memilih mitra infrastruktur berdasarkan transparansi dan keberlanjutan, bukan hanya janji finansial.
Ketiga, ketahanan nasional sebagai tameng kedaulatan. “Roosevelt Corollary” membenarkan intervensi atas alasan “chronic wrongdoing”. NSS 2025, meski kurang eksplisit dalam hal intervensi, menekankan “economic security” dan ketahanan AS sebagai fondasi kekuatan. Bagi Indonesia, pesannya jelas: ketahanan nasional yang komprehensif-meliputi ekonomi, pangan, energi, kesehatan, dan ketahanan sosial-adalah strategi pertahanan terbaik.
Negara dengan fondasi ekonomi yang kuat, tata kelola yang baik, stabilitas politik, dan kohesi sosial yang tinggi jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami krisis yang dapat mengundang tekanan atau intervensi asimetris dari luar. Membangun kemandirian dalam rantai pasok strategis, mendiversifikasi mitra ekonomi, dan memperkuat fondasi industri dan teknologi dalam negeri bukan hanya agenda pembangunan, tetapi juga imperatif keamanan nasional. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi dimana “friendshoring” dan “reshoring” menjadi tren (seperti yang dicanangkan NSS 2025), Indonesia juga harus cerdas memposisikan diri dalam rantai nilai global yang baru.
Keempat, bahaya politisasi retorika geopolitik dan pentingnya narasi strategis sendiri. Doktrin Monroe telah menjadi “kata kunci” yang dipolitisasi. NSS 2025 membingkai ulang konsep “Indo-Pacific” dalam kerangka kompetisi dengan Tiongkok. Indonesia harus berhati-hati dan proaktif dalam narasi strategis kawasan. Konsep seperti “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)” adalah upaya penting untuk mendefinisikan visi kawasan sendiri yang inklusif dan berbasis kerja sama, bukan konfrontasi.
Indonesia perlu terus mendorong dan mengoperasionalkan AOIP, memastikan bahwa konsep geopolitik tidak dikooptasi oleh satu pihak untuk memecah belah ASEAN atau membenarkan pola perilaku eksklusif. Diplomasi Indonesia harus mampu menjelaskan dan “menjual” visi ini secara efektif kepada mitra-mitra eksternal.
Kelima, multilateralisme yang efektif versus unilateralisme yang terbatas. NSS 2025 sangat skeptis terhadap multilateralisme yang dianggap merugikan AS dan mendorong “burden-sharing” yang ketat. Periode ketika Doktrin Monroe sedikit “diredam” adalah saat mekanisme seperti OAS diperkuat. Bagi Indonesia, penguatan platform multilateral seperti ASEAN, East Asia Summit (EAS), dan ARF tetap sangat penting sebagai wadah untuk mengelola hubungan dengan kekuatan besar, menyelesaikan sengketa, dan menjaga keseimbangan.
Keenam, tantangan menghadapi AS dan sekutunya di kawasan Pasifik. Indonesia perlu merumuskan langkah strategis-taktis yang cermat dalam diplomasi dengan negara-negara Pasifik. Bagi AS, kawasan Oseania dianggap sebagai “halaman belakang”-nya, sehingga isu seperti dukungan politik terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam forum MSG dan PIF menjadi tantangan serius. Secara geografis, Tanah Papua termasuk dalam kawasan Pasifik, dan secara demografis memiliki kedekatan etno-kultural dengan bangsa Melanesia di Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, Kaledonia Baru, serta Torres Strait Islanders. Hal ini menuntut pendekatan diplomasi yang tidak hanya responsif, tetapi juga berbasis pada solidaritas kultural dan kepentingan strategis jangka panjang.
Tantangannya adalah membuat institusi-institusi ini tetap relevan, gesit, dan efektif dalam menghasilkan solusi konkret. Indonesia harus menjadi motor reformasi dan revitalisasi institusi regional, agar tidak ditinggalkan oleh tren bilateralisme atau minilateralisme yang selektif seperti “Quad” atau AUKUS, sambil tetap mencari cara untuk terlibat secara konstruktif dengan pengelompokan tersebut.
Doktrin Monroe adalah monumen bagi ambivalensi kekuatan, dan NSS 2025 adalah bab terbaru dalam evolusinya. Ia menunjukkan bahwa di bawah logika “America First”, konsep hemispherik klasik dapat dibangkitkan dan disesuaikan dengan alat-alat kekuatan kontemporer. Kisahnya mengajarkan bahwa prinsip-prinsip kebijakan luar negeri dari kekuatan besar dapat memiliki umur panjang dan adaptif, seringkali dengan konsekuensi yang dalam bagi negara-negara di “lingkar” yang dimaksud.
Bagi Indonesia, refleksi mendalam atas doktrin ini dan manifestasi strategisnya yang baru mempertegas pentingnya jalan mandiri yang waspada dan percaya diri. Masa depan Asia Tenggara tidak boleh ditulis oleh “doktrin” unilateral mana pun, baik dari Barat maupun Timur. Masa depan itu harus dibangun bersama oleh negara-negara ASEAN melalui konsensus, saling menghormati, ketahanan kolektif, dan pengakuan atas agensi setiap bangsa.
Indonesia, dengan kekuatan dan posisinya, memiliki tanggung jawab dan peluang untuk memastikan bahwa resonansi Doktrin Monroe di abad ke-21 tidak menjadi pola yang terulang di kawasan sendiri. Dengan memperkuat ketahanan nasional, mempertahankan solidaritas ASEAN, menavigasi persaingan besar dengan bijak, dan aktif membentuk narasi kawasan, Indonesia dapat mengubah pelajaran dari sejarah geopolitik yang jauh menjadi peta jalan bagi kedaulatan dan kemakmuran di tengah gelombang besar abad ini.