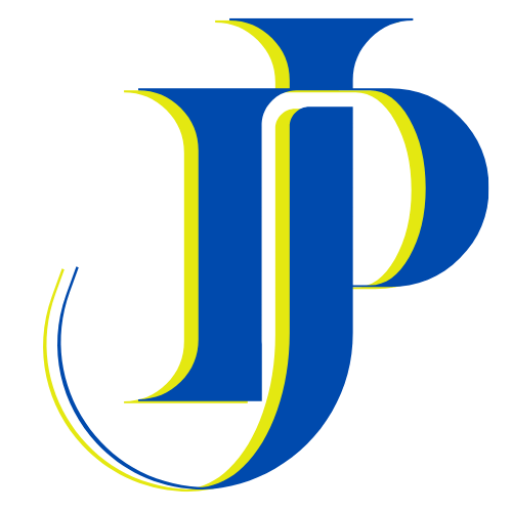Laurens Ikinia
Peneliti di Institute of Pacific Studies; Dosen Hubungan Internasional UKI, Jakarta
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memikul beban janji keberlanjutan pembangunan dan komitmen pembangunan terobosan pada sektor lain.
Sorotan publik tertuju tajam pada komitmen pemberantasan korupsi, yang dijanjikan tidak hanya sebagai retorika, melainkan sebuah arsitektur sistemik berbasis tiga pilar: preventif, detektif, dan represif. Kini, fondasi dari kerangka ambisius itu mulai menunjukkan tanda-tanda konkret.
Sebuah momen simbolis terjadi di Gedung Kejaksaan Agung, Rabu, 24 Desember 2025. Disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi menyerahkan setoran ke negara senilai Rp6,6 triliun.
Angka fantastis ini merupakan akumulasi
dari dua sumber utama: Rp4,28 triliun berasal dari penyitaan dalam penanganan perkara korupsi, khususnya kasus dugaan korupsi fasilitas ekspor CPO dan impor gula; sementara Rp2,34 triliun sisanya merupakan realisasi penagihan denda administratif kehutanan dari 21 perusahaan sawit dan nikel.
Aksi represif ini disertai langkah preventif nyata, yaitu penguasaan kembali kawasan hutan seluas 4,08 juta hektare untuk direhabilitasi. Lebih dari sekadar pencapaian instan, momentum ini menjadi batu pijakan strategis.
Kejagung memetakan potensi penerimaan negara masa depan yang sangat besar, mencapai Rp109,6 triliun dari denda administratif sektor sawit dan Rp32,63 triliun dari sektor tambang di dalam kawasan hutan-sebuah angka yang
mengisyaratkan skala pendeteksian dan pencegahan yang lebih masif.
Namun, narasi penegakan hukum tahun 2025 tidak berhenti di sana. Pilar represif pemerintahan ini juga diuji melalui kasus-kasus besar lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, berhasil menyita aset senilai ratusan miliar rupiah dalam pengungkapan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga melibatkan penetapan tersangka pejabat tinggi.
Di sektor perbankan, Kejaksaan Tinggi Jakarta menangani kasus korupsi kredit bermasalah dengan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah, yang telah berujung pada penangkapan seorang mantan direktur bank pelat merah.
Gelombang penyitaan dan penangkapan bernilai triliunan rupiah ini menjadi penanda awal yang krusial. Ia mengirim pesan keras sekaligus membangun fondasi akuntabilitas.
Tantangan sesungguhnya tetap terbentang: memastikan bahwa momentum penindakan ini berkelanjutan, terintegrasi dengan sistem pencegahan yang andal, dan pada akhirnya bukan hanya menambah pundi-pundi negara, tetapi secara fundamental mengikis kultur koruptif yang telah berakar.
Janji pemerintahan baru sedang dipertaruhkan pada transisi dari retorika menjadi aksi yang konsisten dan tanpa tebang pilih. Di ranah pencegahan, benang kebijakan konkret mulai dirajut dengan hati-hati. Wacana tak lagi melayang dalam abstraksi, tetapi menyentuh tanah. Pemerintahan ini menggariskan integrasi
modul nilai integritas dan etika publik ke dalam kurikulum pendidikan dasar-sebuah investasi jangka panjang untuk menanamkan antibodi moral sejak dini.
Secara paralel, program pelatihan etika yang menyeluruh dan berjenjang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) digariskan,
bertujuan memperkuat benteng pertahanan dari dalam birokrasi itu sendiri. Sementara di garis depan deteksi, fokus diarahkan pada modernisasi sistem pengawasan.
Andalan diletakkan pada pemanfaatan big data analytics dan kecerdasan buatan, yang
diharapkan menjadi mata-mata digital yang tak pernah lelap. Sistem ini dirancang untuk memetakan anomali, melacak pola transaksi mencurigakan, dan memberi peringatan dini secara real-time di dalam tubuh birokrasi yang kompleks-sebuah transformasi pengawasan dari yang reaktif menjadi proaktif.
Namun, yang paling mencolok dan segera menjadi ciri khas fase awal pemerintahan ini bukan semata pada blueprint teknisnya, melainkan pada framing politik yang dibangun dengan sengaja.
Presiden Prabowo, dengan kapital simbolisnya sebagai mantan jenderal, secara konsisten menaikkan derajat ancaman korupsi dari sekadar economic crime menjadi “ancaman terhadap kedaulatan nasional.”
Dalam narasi yang dibangunnya, praktik korupsi disetarakan dengan tindakan makar-sebuah pengkhianatan yang diam-diam menggerogoti dana publik dan melemahkan ketahanan negara dari dalam.
Narasi heroik dan militeristik ini berhasil
membangkitkan resonansi emosional yang kuat, khususnya di kalangan konstituen yang mendambakan ketegasan. Meski demikian, di balik gelora nasionalistik itu, para pengamat kebijakan, akademisi hukum dan aktivis antikorupsi veteran menyimpan catatan kehati-hatian.
Mereka memperingatkan bahwa narasi yang terlalu bersandar pada diksi perang dan keamanan nasional adalah pedang
bermata dua. Potensi penyalahgunaan selalu mengintai: bisa dialihfungsikan sebagai alat pembungkus agenda politik yang sempit, atau—yang lebih berbahaya—sebagai instrumen untuk mengkriminalisasi oposisi dan mengaburkan batas antara pelanggaran hukum dengan pengkhianatan negara.
Peringatan ini menempatkan sebuah tantangan tersendiri: bagaimana menjaga kemurnian agenda reformasi agar tidak terkontaminasi oleh logika kekuasaan yang
justru ingin dibersihkan.
Ujian Integritas di Tengah Koalisi Gemuk
Membaca janji dari naskah pidato adalah satu hal; menjalankannya di lapangan kartel politik Indonesia yang rumit dan sudah berurat akar adalah cerita yang sama sekali berbeda. Tantangan terberat bagi Presiden Prabowo, secara paradoks, justru akan datang dari dalam rumah kekuasaannya sendiri.
Koalisi “gemuk” yang memberinya stabilitas politik dan mayoritas nyaman di parlemen, secara inheren rentan menjadi lahan subur bagi kompromi, transaksi, dan politik balas jasa. Inilah dilema klasik pemerintahan koalisi besar di Indonesia.
Tekanan internal dari partai-partai pendukung, yang datang secara halus maupun terang-terangan untuk melindungi kadernya yang tersangkut jerat hukum, akan menjadi barometersesungguhnya dari integritas pemerintahan ini.
Kemampuan Presiden untuk menolak intervensi tersebut dengan tegas, atau sebaliknya, tunduk pada logika transaksional yang ia kecam, akan menjadi penentu kredibilitas seluruh narasi heroik antikorupsinya.
Ujian krusial lainnya terletak pada komitmen terhadap restorasi kelembagaan. Narasi kuat perlu ditopang oleh institusi yang kuat. Independensi badan penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus diletakkan di atas segala kepentingan politik jangka pendek.
Namun, bayang-bayang amandemen UU KPK beberapa tahun silam yang dinilai
banyak pihak telah membelenggu kewenangan dan memperlambat laju lembaga masih menghantui seperti trauma kolektif.
Pemerintahan ini tidak hanya dituntut aktif mengejar kasus-kasus besar (high-profile cases), tetapi lebih mendasar lagi, ditantang untuk melakukan pekerjaan restorasi yang kurang seksi: memperkuat fondasi kelembagaan antikorupsi itu sendiri.
Ini memerlukan political will yang jauh lebih besar dan berisiko. Pilihannya adalah antara menjadi pemadam kebakaran yang heroik saat kobaran api terlihat, atau menjadi insinyur yang memperbaiki sistem hidran dan instalasi listrik yang sudah lapuk untuk mencegah kebakaran sejak awal.
Maraton Restorasi
Perjalanan memberantas korupsi di Indonesia kerap diibaratkan sebagai upaya merestorasi sebuah katedral agung yang tua. Dibutuhkan tidak hanya semprotan air bertekanan untuk membersihkan lumut di permukaan, tetapi juga keberanian menggali hingga ke fondasi terdalam, membongkar struktur yang keropos dan mengusir koloni rayap yang telah lama
bersarang.
Pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan narasi keberanian politik dan langkah sistemik awalnya, telah menarik garis start yang baru di sebuah lapangan yang penuh lubang dan rintangan.
Masyarakat sipil yang skeptis namun penuh harap mencatat dengan saksama setiap
gerak-gerik. Komunitas internasional menunggu dengan skeptisisme yang terbuka.
Pertanyaan besar yang menggantung adalah: apakah gelora awal ini akan bermetamorfosis menjadi reformasi hukum yang berkelanjutan, adil, dan benar-benar imparsial? Ataukah ia akan meredup perlahan, tenggelam dalam ritual konsolidasi kekuasaan dan godaan untuk berdamai dengan status quo?
Jawabannya tidak akan datang dalam satu atau dua tahun. Ia akan terukir dalam serangkaian keputusan keras yang tidak populer di internal koalisi, dalam komitmen anggaran untuk modernisasi sistem yang tidak terlihat mata, dan dalam keteguhan menolak godaan untuk menggunakan aparatus antikorupsi sebagai alat politik.
Legasi Presiden kedelapan Indonesia
akan sangat ditentukan oleh kapasitasnya mengarahkan narasi keberanian menjadi energi yang membangun institusi, bukan sekadar menghancurkan lawan.
Pada akhirnya, pertarungan melawan korupsi adalah sebuah maraton, bukan lari sprint seratus meter. Di bawah pemerintahan yang baru, pistol starter telah berbunyi dengan gemuruh.
Sorak-sorai di garis start bisa terdengar memekakkan telinga. Namun, lintasan yang harus ditempuh amatlah panjang, berkelok, dan menanjak. Lintasan itulah yang akan membuktikan hakikat perjalanan ini. Sejarah, sang pencatat waktu yang paling sabar dan paling kejam sedang
mencatat setiap langkahnya.
Namun, di balik struktur tiga pilar yang rapi dan narasi heroik yang menggema, terdapat medan pertarungan yang lebih halus dan mungkin lebih menentukan: pertarungan melawan normalisasi korupsi.
Korupsi di Indonesia telah berevolusi menjadi suatu ekosistem yang kompleks, di mana praktik pungutan liar, gratifikasi yang dimaklumi dan nepotisme yang
dikemas sebagai gotong royong telah menyusup ke dalam budaya birokrasi dan masyarakat.
Tantangan sesungguhnya bagi arsitektur sistemik ini adalah kemampuannya menjangkau dan membongkar tidak hanya korupsi yang spektakuler, tetapi juga korupsi yang sunyi dan sistemik
ini.
Modul integritas dalam kurikulum akan berhadapan dengan realitas di mana anak-anak mungkin menyaksikan orang tua mereka menyelesaikan urusan dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai di sekolah.
Pendekatan berbasis teknologi, meski canggih, membawa risiko reduksionis data bisa menunjukkan anomali angka, namun tidak selalu menangkap nuansa konteks atau tekanan sistemik.
Oleh karena itu, kesuksesan paradigma ini tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diungkap. Ia harus diukur dari kemampuannya melakukan transformasi kultural pergeseran dari masyarakat yang secara pasif menerima korupsi sebagai biaya administrasi, menjadi masyarakat yang secara aktif menolak, melapor dan menjunjung integritas sebagai nilai non-
negotiable.
Ini adalah pekerjaan yang melibatkan tidak hanya negara, tetapi juga desakan dari
keluarga, komunitas, dunia usaha, dan media. Tanpa transformasi di tingkat akar rumput ini, arsitektur sistemik yang megah berisiko menjadi menara gading efektif menangkap tikus-tikus besar yang terlihat, sementara rayap-rayap kecil di bawahnya terus menggerogoti fondasi bangsa tanpa henti.
Inilah maraton sesungguhnya: lomba melawan waktu dan latennya budaya untuk menciptakan sebuah tatanan di mana integritas bukan lagi pilihan heroik melainkan satu-satunya jalan yang mungkin.