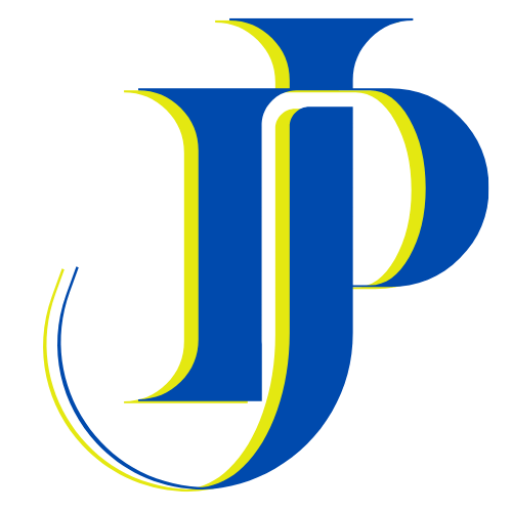Laurensius Bagus
Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Survei terbaru Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) kembali menyalakan tanda bahaya bagi arah demokrasi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan lebih dari separuh responden menilai kualitas demokrasi dalam beberapa tahun terakhir justru mengalami kemunduran. Angka itu menegaskan kegelisahan publik yang kian nyata: demokrasi Indonesia berjalan di tempat, jika bukan maju, malah mundur.
Temuan LP3ES bukan sekadar hasil survei rutin, melainkan cermin dari krisis kepercayaan yang semakin dalam terhadap praktik politik dan institusi negara. Publik menilai kebebasan sipil semakin terbatas, kekuasaan eksekutif terlalu dominan, dan lembaga pengawasan kehilangan taring. Demokrasi yang seharusnya tumbuh dari partisipasi rakyat kini lebih banyak dijalankan dalam ruang-ruang elitis yang steril dari kontrol publik.
Fenomena stagnasi ini juga tampak dari indeks demokrasi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam laporan tahun 2023, skor Indeks Demokrasi Indonesia berada di angka 74,44 — hanya naik tipis dari tahun sebelumnya dan masih di bawah puncaknya satu dekade lalu. Artinya, meski secara prosedural demokrasi tetap berjalan — dengan pemilu, partai politik, dan kebebasan pers — kualitas substansinya terus menurun. Demokrasi kita tampak hidup di permukaan, namun lemah di jantungnya.
Salah satu penyebab utama kemunduran ini adalah menurunnya kualitas institusi politik. Partai politik, yang seharusnya menjadi sarana pendidikan politik rakyat, lebih sibuk menjaga kedekatan dengan kekuasaan. Rekrutmen politik masih didominasi figur-figur bermodal besar, bukan gagasan besar. Elite partai lebih sering menjadi perpanjangan tangan pemerintah ketimbang menjadi pengontrol kebijakan. Akibatnya, oposisi kehilangan daya tawar, dan ruang kritik terhadap kekuasaan semakin menyempit.
Kondisi itu diperparah oleh memburuknya penegakan hukum dan independensi lembaga yudikatif. Sejumlah survei lembaga riset politik menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap integritas lembaga hukum terus menurun. Publik semakin skeptis terhadap penegakan hukum yang kerap dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ketika keadilan menjadi barang langka, maka demokrasi pun kehilangan pondasi moralnya.
Kebebasan sipil salah satu indikator utama demokrasi juga mengalami tekanan. Beberapa lembaga pemantau mencatat peningkatan kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dalam lima tahun terakhir. Aktivis, jurnalis, dan akademisi sering kali menjadi sasaran intimidasi atau kriminalisasi hanya karena menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Di media sosial, buzzer politik bekerja secara sistematis membentuk opini publik dan membungkam suara berbeda. Demokrasi digital berubah menjadi arena propaganda yang mematikan dialog publik.
Krisis kepercayaan ini juga merembes ke masyarakat. Menurut survei LP3ES, hanya sekitar 30 persen responden yang percaya bahwa pemerintah benar-benar mendengar aspirasi rakyat. Angka ini memperlihatkan jarak yang semakin lebar antara penguasa dan warga. Demokrasi kehilangan maknanya ketika keputusan publik diambil tanpa partisipasi nyata dari mereka yang terdampak.
Fenomena stagnasi demokrasi di Indonesia bukan semata soal buruknya perilaku elite, tetapi juga lemahnya pendidikan politik masyarakat. Demokrasi yang sehat memerlukan warga yang kritis, rasional, dan partisipatif. Namun kenyataannya, banyak warga yang terjebak dalam politik transaksional. Pemilu masih dipahami sebagai momen tukar-menukar suara dengan uang atau bantuan. Politik identitas dan populisme murahan tetap menjadi alat efektif untuk merebut simpati publik.
Sementara itu, media pilar keempat demokrasi berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, media berperan penting menjaga transparansi dan mengawasi kekuasaan. Namun di sisi lain, tekanan ekonomi dan politik membuat sebagian media kehilangan independensinya. Kepemilikan media yang terkonsentrasi di tangan segelintir elite bisnis-politik mempersempit keragaman suara. Ketika ruang publik didominasi oleh kepentingan modal dan kekuasaan, wacana kritis menjadi barang langka.
Namun, stagnasi ini bukan akhir dari cerita. Justru di tengah kemunduran, muncul peluang untuk refleksi dan perbaikan. Demokrasi tidak akan pernah sempurna, tetapi ia harus terus diperjuangkan. Reformasi institusi politik menjadi agenda mendesak mulai dari pembenahan sistem partai, transparansi pendanaan politik, hingga penguatan lembaga pengawasan seperti KPK dan Ombudsman. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi ritual lima tahunan tanpa makna substantif.
Selain reformasi struktural, demokrasi juga membutuhkan energi moral dari masyarakat sipil. Gerakan sosial, komunitas warga, akademisi, dan media independen harus kembali memainkan peran korektifnya. Mereka menjadi penyeimbang di tengah kecenderungan kekuasaan yang kian sentralistik. Dalam konteks ini, survei LP3ES bukan sekadar data statistik, melainkan alarm moral agar bangsa ini tidak terbiasa dengan kemunduran.
Kita tak bisa menunggu elite berubah tanpa tekanan publik. Demokrasi hanya akan hidup jika warga berani bersuara, menuntut transparansi, dan mempertanyakan keputusan yang tidak adil. Keberanian sipil adalah oksigen demokrasi tanpanya, sistem politik akan mudah tersedak oleh kepentingan sempit.
Dalam pandangan yang lebih luas, stagnasi demokrasi Indonesia mencerminkan ujian bagi konsolidasi pascareformasi. Dua puluh lima tahun setelah tumbangnya Orde Baru, kita belum sepenuhnya berhasil membangun demokrasi yang matang. Perubahan politik memang telah membawa kebebasan, tetapi kebebasan itu kini dihadapkan pada ancaman baru: pragmatisme, apatisme, dan kooptasi kekuasaan.
Maka, pertanyaannya kini bukan lagi apakah demokrasi kita hidup, tetapi apakah ia masih sehat. Jawaban atas pertanyaan itu tergantung pada sejauh mana rakyat dan elite politik mampu mengembalikan demokrasi pada hakikatnya: sistem yang melindungi kebebasan, menegakkan keadilan, dan mendengarkan suara rakyat. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi nama kosong berdiri megah, tetapi rapuh dari dalam.