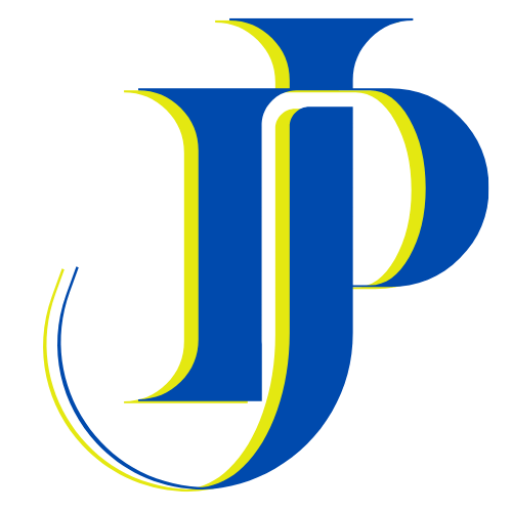DALAM filsafat Tionghoa kuno, terdapat sebuah pepatah yang sederhana namun dalam maknanya: “Segala sesuatu berkumpul menurut jenisnya, manusia pun berkelompok menurut golongannya.”
Di dunia Barat, kita mengenal ungkapan serupa: “Tell me who your friends are, and I’ll tell you who you are.”
Kedua pepatah ini menggarisbawahi satu hal: seseorang sering kali mencerminkan karakter lingkungan berpikir dan pergaulannya.
Kebijaksanaan kuno itu terasa relevan ketika menyaksikan polemik seputar tudingan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang kembali mencuat.
Meski telah berkali-kali dibantah oleh universitas dan melalui klarifikasi resmi negara, isu ini terus berputar, berpindah tangan, dan menemukan penggemarnya di sudut-sudut ruang digital yang haus sensasi.
Dalam pusaran itu, nama-nama tertentu muncul bukan hanya sebagai individu, melainkan juga sebagai cermin dari sebuah ekosistem berpikir—ruang di mana kecurigaan tumbuh lebih cepat daripada verifikasi.
Pepatah Tionghoa tadi mengajarkan bahwa manusia cenderung berkumpul dengan mereka yang memiliki kesamaan nilai, keyakinan, atau emosi.
Di era digital, pepatah itu menemukan bentuk barunya: kita kini “berteman” bukan hanya dalam kehidupan nyata, tetapi juga dalam pola pikir, algoritma, dan gelembung informasi.
Setiap kali seseorang membagikan narasi yang belum teruji, ia bukan hanya menegaskan sikapnya terhadap suatu isu, tetapi juga mencerminkan kualitas lingkaran berpikir tempat ia bernaung.
Dalam kasus polemik ijazah ini, terlihat jelas bagaimana media sosial menjadi arena pertemuan antara skeptisisme rasional dan skeptisisme emosional. Yang pertama lahir dari keingintahuan ilmiah; yang kedua tumbuh dari ketidakpercayaan yang telah mengeras.
Perbedaan keduanya terletak pada satu hal: keberanian untuk menimbang fakta, bukan hanya mengulang prasangka. Di sinilah pentingnya menyadari bahwa “teman berpikir” kita—baik manusia maupun sumber informasi—pada akhirnya membentuk wajah nalar kita.
Krisis kebenaran di era post-truth bukan sekadar persoalan data yang salah, melainkan juga tentang ikatan sosial yang terbangun dari kesalahan itu. Ketika sekelompok orang saling menguatkan keyakinan yang sama tanpa dasar bukti, kebenaran digantikan oleh solidaritas perasaan.
Kita tak lagi mencari kebenaran, melainkan mencari teman yang berpikir seperti kita. Inilah momen ketika pepatah Tionghoa itu berubah dari peringatan menjadi potret nyata: manusia memang berkelompok menurut golongannya—bahkan dalam hal salah paham.
Namun, refleksi ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi siapa pun. Justru sebaliknya, ia mengingatkan kita bahwa dalam masyarakat yang terpolarisasi, kemampuan menjaga kejernihan berpikir adalah sebuah bentuk kebijaksanaan baru.
Skeptisisme tetap diperlukan, tetapi tanpa kebencian. Klarifikasi tetap penting, tetapi tanpa arogansi. Di antara dua kutub itu, kebenaran hanya dapat bertahan jika disertai kerendahan hati untuk mendengar.
Pepatah lama itu, jika dibaca ulang, bukanlah ajakan untuk memilih teman berdasarkan status sosial atau politik, melainkan panggilan untuk berhati-hati dalam memilih ruang pikir.
Sebab, siapa pun yang kita dengarkan, kita serap, dan kita percayai—sedikit demi sedikit—membentuk diri kita.
Maka, di tengah riuhnya tudingan dan klarifikasi, mungkin yang paling bijak adalah bertanya kepada diri sendiri: Dengan siapa aku berpikir? Dengan siapa aku mencari kebenaran?
Dalam suasana seperti itu, kebenaran bukan lagi sekadar pertarungan opini, melainkan hasil dari disiplin intelektual dan kematangan moral.
Di sanalah letak kebijaksanaan yang tak lekang waktu—dari pepatah Tionghoa ribuan tahun lalu hingga dunia digital hari ini—bahwa manusia dinilai bukan hanya dari siapa ia berteman, tetapi dari siapa ia mempercayai pikirannya.