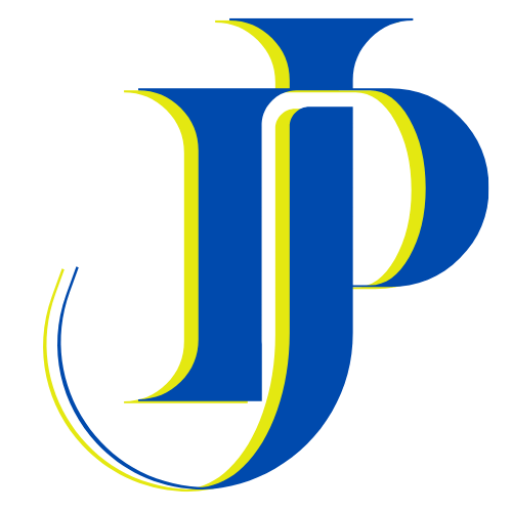Melki Deni, S. Fil.
Mahasiswa Teologi di Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Spanyol
Menurut Byung-Chul Han, masyarakat neoliberal dan euforianya yang berlebihan terhadap kerja dan perwujudan diri tak terelakkan mengembangkan agresi diri yang ditandai oleh kepositifan “you can do it!”, di mana kekerasan kini dilakukan terhadap diri sendiri dalam bentuk seruan terus-menerus untuk menjadi lebih produktif, berprestasi, dan bekerja lebih keras menuju optimalisasi diri.
Beginilah cara seseorang mengeksploitasi diri. Upaya-upaya pribadi ini, meskipun menghasilkan rasa “autentisitas”, segera tertuju ke ranah narsisme, yaitu ke logika “aku”. Dengan demikian, tekanan untuk berproduksi dan berprestasi mengintensifkan dan mempercepat proses individuasi.
Dilihat dari sudut pandang ini, dorongan untuk memperbaiki diri, sebagai modus produksi neoliberal, dan rasa autentisitas yang tak terelakkan yang menyertainya, diwujudkan sebagai pabrik narsisis yang efisien yang hanya peduli pada keuntungannya sendiri, sama sekali buta terhadap rasa kebersamaan atau “kita”—kekitaan.
Byung-Chul Han, dalam La desaparición de los rituales, menjelaskan: “autentisitas merepresentasikan suatu bentuk produksi neoliberal. Seseorang secara sukarela mengeksploitasi dirinya sendiri, meyakini bahwa dirinya telah mencapai kepuasan.
Melalui kultus autentisitas, rezim mengapropriasi pribadi seseorang, mengubahnya menjadi pusat produksi dengan efisiensi yang superior. Dengan cara ini, seluruh pribadi terlibat dalam proses produksi. Kultus autentisitas merupakan tanda yang tak terbantahkan dari kemerosotan sosial […] Tekanan untuk menjadi autentik mengarah pada introspeksi narsistik, pada kekhawatiran permanen terhadap psikologi diri.”
Kultus autentisitas ini menghasilkan absolutisasi kinerja personal dan atomisasi kolektif, karena dalam pencarian autentisitas diri yang melelahkan, subjek kinerja mendapati dirinya sendirian tanpa bisa diperbaiki.
Autentisitas adalah perasaan yang bersifat narsis. Dilihat dengan cara ini, melalui “kultus diri” dan meningkatnya narsisme, rezim neoliberal meresmikan hilangnya rasa “kita” secara menyedihkan.
Nilai-nilai kolektif, seperti solidaritas dan empati, pada hakikatnya hilang. Modus produksi neoliberal didasarkan pada penghancuran ikatan sosial untuk menghasilkan individu-individu yang terisolasi dan menyendiri. Komunitas atau kepedulian terhadap sesama tidak sesuai dengan ekonomi neoliberal, yaitu dengan sistem ekonomi “aku” dan “kami”.
Byung-Chul Han, dalam Vida Contemplativa. Elogio a la Inactividad, 2023, menegaskannya begini: “Kesendirian wirausahawan, terisolasi dan terindividualisasi, merupakan bentuk produksi saat ini (…) Saat ini, semua orang bersaing satu sama lain, bahkan di dalam perusahaan yang sama. Persaingan absolut ini sangat meningkatkan produktivitas tetapi menghancurkan solidaritas dan kesopanan.”
Ketiadaan nilai-nilai kolektif dan meluasnya ketidakpedulian terhadap sesama merupakan proses yang saling berkaitan. Sang “wirausahawan mandiri”, yang terobsesi dengan kinerja dan optimalisasi diri, mau tidak mau melupakan “kita”.
Seluruh hidupnya terbatas pada pekerjaan yang terus-menerus. Ia tak lagi mampu berdialog mendalam dengan orang lain dan tak lagi tahu bagaimana membicarakan topik lain selain pekerjaan. Kini bahkan bahasa pun tunduk pada logika produksi neoliberal dan kinerja pribadi, dan inilah bagaimana kata-kata yang murni bersifat ekonomi, seperti investasi, pertumbuhan, dan laba, berkembang biak.
Kinerja pribadi yang berlebihan tidak menemui batasan atau perlawanan yang pasti. Subjek mengeksploitasi diri sendiri sesuai dengan perintahnya sendiri. Tekanan untuk berproduksi dan berprestasi bukanlah sesuatu yang datang dari luar dan menekan subjek, sebaliknya, tekanan tersebut didasarkan pada kebutuhan internal yang justru memperkuat cangkang narsistik diri.
Dalam logika neoliberal yang licik ini, yang membawa eksploitasi diri ke tingkat yang dahsyat, Byung-Chul Han memperingatkan, “Eksploitasi tanpa Penguasaan” menjadi mungkin. Saat ini tidak ada otoritas eksternal yang memaksa subjek untuk histeria kinerja, dan kebutuhan ini disebabkan oleh kompulsi narsistik, dalam bentuk eksploitasi diri secara sukarela.
Cara hidup sepenuhnya ditentukan oleh kerja dan produksi, namun berbahaya untuk menganggap penentuan ini sebagai satu-satunya cara hidup. Kehidupan harus mengasumsikan dalam dirinya sendiri cara hidup lain yang mampu menyingkirkan dan membebaskan manusia dari ekosistem neoliberal yang berlaku, yang didominasi oleh kinerja dan optimalisasi absolut.
Merupakan tugas politik untuk mengarahkan kehidupan ke cara hidup lain di mana narsisme dan penyerahan diri sepenuhnya diatasi. Pada akhirnya, ini tentang mengembalikan sukacita umat manusia dalam ketidakaktifan, pesta, dan “bersama” orang lain.
Penting, bahkan merevitalisasi, untuk belajar menempatkan eksistensi dalam “waktu orang lain”, yang, seperti dikemukakan Byung-Chul Han, menebus subjek narsisistik dari hubungan agresif dan eksploitatif yang dijalinnya dengan dirinya sendiri.
Namun mengingat absolutisasi yang membabi buta atas eksploitasi diri demi kinerja dan optimalisasi, yang pada akhirnya mengubah kita menjadi individu yang terisolasi, kita tidak lagi mampu hidup bersama orang lain, “ada bersama” dalam koeksistensi tanpa pamrih.
Kita hanya tahu bagaimana memaknai hidup dalam konteks kerja, produktivitas, dan keuntungan kita sendiri; beginilah cara kita hidup saat ini tanpa mengenal siapa sesama kita. Kinerja kita sendiri membutakan kita terhadap koeksistensi dengan orang lain, yang kini kita anggap sebagai kehadiran yang tidak nyaman, hambatan yang tidak diinginkan bagi pemenuhan diri kita.
Kita terisolasi dalam ambisi kita. Kita tidak lagi bergaul dengan orang lain. Kita telah sepenuhnya kehilangan rasa kebersamaan, pesta, dan komunitas. Inilah bagaimana kita juga kehilangan rasa kemanusiaan dan empati.
Krisis moral diperparah oleh sistem produksi ekonomi neoliberal yang berlaku. Oleh karena itu, mengikuti Byung-Chul Han, adalah bijaksana untuk membandingkan waktu pesta dan waktu orang lain dengan desakan neoliberal untuk kinerja dan optimalisasi pribadi.
Pesta itu sendiri meresmikan logika temporalnya sendiri, dan waktu “kita”lah yang memisahkan waktu “aku”. Dan karena itu waktu itu menjadi waktu yang baik, waktu yang layak dijalani. “Revolusi Temporal” yang mendesak melibatkan kebangkitan waktu “kita”, waktu komunitas, dan pesta.
Dalam dalam La Expulsión de lo Distinto, Byung-Chul Han menggambarkan: “Politik temporal neoliberal menghilangkan waktu orang lain, yang dengan sendirinya akan menjadi waktu yang tidak produktif.
Totalisasi waktu diri disertai dengan totalisasi produksi, yang saat ini mencakup semua bidang kehidupan dan mengarah pada eksploitasi total umat manusia. Politik temporal neoliberal juga menghilangkan waktu pesta, waktu pernikahan yang agung, yang tidak tunduk pada logika produksi. Ini mengarah pada penghapusan produksi.
Tidak seperti waktu diri, yang mengisolasi dan mengindividualisasikan kita, waktu orang lain menciptakan komunitas. Itulah mengapa ini adalah waktu yang baik.” Waktu orang lain dilihat sebagai ancaman terhadap waktu “saya” dan “ke-kami-an”. Waktu orang lain harus menyesuaikan atau menyerahkan diri kepada waktu “saya” dan “ke-kami-an”.
Pesta menghasilkan pembebasan dari beban kinerja dan tekanan narsisme, membebaskan individu dari pikiran dan kesibukan sehari-hari. Pesta adalah kongres bahagia yang mengabaikan kediktatoran kesehatan yang kurang ajar. “Dalam pesta”, kata Byung-Chul Han, “hidup memperoleh intensitas tertentu,” bahkan ekses dan ketidaksederhanaan tertentu.
Dalam pesta, hidup itu sendiri dilepaskan dari segala tujuan, tak lagi terbatas pada dimensi ruang dan produksi. Selama pesta, ekses dan pelanggaran berkuasa, yang membentuk bentuk-bentuk kehidupan yang berdaulat.
Itulah sebabnya saat ini, di tengah ekstase produktivitas dan kerja, pesta bersinar dengan aura penebusan. Ia menjadi penebusan par excellence. Ia menghasilkan “pelucutan senjata diri”. Sebuah desentralisasi radikal dari dimensi kerja dan pencapaian.
Dalam absolutisasi produksi dan kinerja, kehidupan, menurut Byung-Chul Han, terdegradasi menjadi sekadar bertahan hidup. Mereka yang membaktikan diri untuk bertahan hidup tak lagi bisa merayakan atau menikmati hidup. Seluruh energi mereka terfokus pada bekerja dan berkarya.
Mereka tak lagi punya waktu untuk berkumpul atau berpesta. Kehidupan yang dibiarkan tanpa pesta, ekses, atau pelanggaran kehidupan sehari-hari adalah kehidupan yang basi, sama sekali tanpa daya tarik.
Kehidupan ini merepresentasikan atrofi eksistensi yang absolut. Kenyataannya sungguh tragis bahwa modus produksi neoliberal telah mengambil dari kita esensi manusia yang mendasari berkumpul, berpesta, dan ekses.
Bahkan hingga hari ini, kita telah kehilangan kapasitas untuk tertawa sejati. Kehidupan saat ini tak mampu “merujuk pada dirinya sendiri” untuk menarik diri. Makna pesta justru adalah pemulihan intensitas dan kegembiraan eksistensi yang saat ini tak terpuaskan terdegradasi oleh produksi, kerja, dan kinerja pribadi.
Pesta mengembalikan kehidupan dan karakter bahagianya, Byung-Chul Han menulis bukunya La desaparición de los rituales: “Dalam pesta sebagai permainan kehidupan, merepresentasikan dirinya sendiri. Ia memiliki karakter ekses yang khas. Ia merupakan ekspresi dari kehidupan yang meluap-luap tanpa tujuan. Itulah intensitasnya. Ia merupakan bentuk kehidupan yang intensif.
Dalam pesta, kehidupan merujuk pada dirinya sendiri, alih-alih menundukkan dirinya pada tujuan eksternal. Itulah sebabnya waktu, yang, seperti halnya saat ini, sepenuhnya didominasi oleh tekanan untuk berproduksi, adalah waktu tanpa pesta. Kehidupan menjadi miskin, stagnan dalam upaya bertahan hidup semata-mata.”
Pesta juga merupakan contoh komunitas. Esensinya adalah kolektif kekitaan. Dalam pesta, kehidupan dirayakan dan komunitas menjadi kongres yang, bagaimanapun juga, membebaskan subjek dari kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, “beban utang” dan ambisi sehari-hari.
Ia merenggut waktu dari totalisasi produksi dan kerja. Dalam waktu pesta, “berlalunya waktu diatasi”, karena yang dirayakan adalah kebutuhan fundamental manusiawi kita yakni kegembiraan, kebahagiaan. Beginilah cara waktu pesta memungkinkan kita untuk ada.
Ia menghasilkan pesona baru yang membahagiakan akan kehidupan dan eksistensi. Dalam pesta pun, tidak ada ruang untuk memikirkan kerja atau kinerja, dan juga tidak ada ruang untuk isolasi narsisistik antara kinerja dan optimalisasi.
Sosok subjek yang berkumpul di sebuah pesta adalah sosok inti komunitas dan oleh karena itu, penebusan dari histeria neoliberal untuk absolutisasi produksi dan kerja. Namun (mengikuti) pesta terus-menerus juga adalah banal, karena hanya membunuh waktu yang dianugerahkan, dan mempersingkat kehidupan.
Pesta merupakan perayaan syukur, penuh rahmat, dan kegembiraan. Itulah sebabnya di kampung-kampung pesta tidak dibuat atau dirayakan setiap saat, tetapi waktu pesta ditentukan berdasarkan kesepakan bersama. Waktu pesta di kampung membutuhkan kesabaran untuk menanti yang produktif, dan kreatif, di mana setiap orang bekerja untuk dapat mengambil bagian dalam perayaan pesta syukuran itu.
Logika temporal pesta ini terletak pada “keabadiannya”. Waktu tak lagi mengalir atau berlalu; sampai batas tertentu, ia telah berhenti. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa waktu tak lagi terikat oleh tujuan atau finalitas apa pun. Ia sepenuhnya terlepas dari euforia produksi, bahkan aktivitas atau “berbuat”.
Ia adalah waktu dan kehidupan yang berdaulat. Intensitas dan ekses adalah pilar-pilar parokialnya. Menurut Han, dalam cara pesta berada, manusia menyerupai para Dewa. Mereka mendekati yang ilahi. Dan mereka terbebas dari imperatif neoliberal produksi dan kinerja.
Dengan logika ini, perlu untuk menginvestasikan waktu pesta dengan dimensi politik. Perlu untuk membayangkan pesta politik yang menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi keberadaannya. Sebuah waktu yang merangkul komunitas yakni “kekitaan”, melampaui “ke-kami-an” kami. Ketika seseorang mengakui dan melegitimasi waktu orang lain, waktu diri, sebagai waktu untuk berprestasi dan mengeksploitasi diri, berakhir.
Tepatnya, revolusi temporal, yang saat ini menjadi penting dan menyegarkan, harus mendorong pembentukan waktu pesta dan komunitas, ketenangan dan ketenteraman. Hanya waktu seperti itu yang akan membawa kontemplasi ke dalam keberadaan dan aroma ke dalam waktu.
Akan tetapi pesta syukuran di kampung-kampung sedang kehilangan makna syukuran, gembira, dan bahagianya, karena hampir setiap orang memegang Ponsel Pintar, melakukan Selfi, merekam video, membuat siaran langsung, menonton video atau foto di media sosial, dan seterusnya.
Setiap orang menjadi narasumber berita sekaligus kantor berita, yang mana mereka memberitakan atau membuat siaran langsung apa yang sedang terjadi. Pembawa acara pun membawa acara terkesan tergesa-gesa karena dorongan untuk scrolling Ponsel Pintar, memberi informasi dan membalas pesan masuk atau komentar di media sosial.
Notifikasi media sosial dan iklan di Ponsel Pintar mengganggu konsentrasi, kekhusyukan, kekhidmatan, dan kesucian perayaan syukur, doa-doa dan ritus-ritus di hadapan roh-roh nenek moyang, dan pesta pada umumnya.
Tidak lagi punya kesabaran dan kemampuan untuk saling mendengarkan: Semua orang berbicara tanpa henti karena didesak oleh sistem notifikasi dan rezim informasi. Adalah bijaksana untuk memiliki harapan di waktu yang secara radikal berbeda dari yang kita kenal dan hidupi sekarang ini.
Byung-Chul Han dalam Por favor cierra los ojos. A la búsqueda de otro tiempo diferente menegaskan: “Saat ini, revolusi waktu dibutuhkan, revolusi yang menghasilkan waktu lain, waktu yang lain, yang bukan waktu kerja, revolusi waktu yang mengembalikan aromanya”.
Revolusi waktu yang dimaksudkan ini lebih berciri sosial, manusiawi dan kultural. Revolusi waktu mendorong kita memahami bahwa kita “memiliki waktu”, tidak hanya tinggal di dalam waktu, mempermainkan waktu. Tanpa berani melakukan revolusi waktu, kita menjadi “hidup di luar diri”, di luar kendali untuk transformasi.