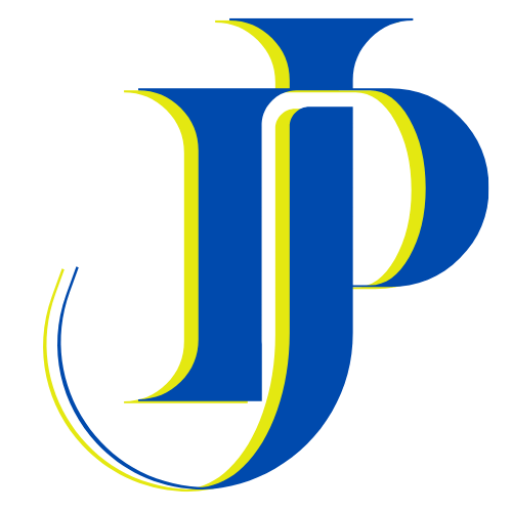Laurens Ikinia
Peneliti Institute of Pacific Studies; Dosen Hubungan Internasional UKI, Jakarta
Di balik gemerlap dan kemacetan Ibu Kota, di balik gedung-gedung pencakar langit yang menjadi simbol kemajuan, Jakarta menyimpan cerita lain. Sebuah cerita tentang ketahanan hati dan mimpi yang tumbuh di tempat-tempat tak terduga.
Di Cilincing, Jakarta Utara, di bawah kolong jembatan penyeberangan, suara riang anak-anak belajar justru menggema, memecah kesunyian ruang yang sering kali dianggap sebagai simbol keterpinggiran.
Ini adalah Rumah Belajar Merah Putih (RBMP), sebuah oase pendidikan bagi puluhan anak dari keluarga dengan ekonomi paling rentan. Dipimpin oleh seorang psikolog, Desi Purwatuning, yayasan ini bertahan dengan ketulusan para pengajar muda dan donasi seadanya. Di sini, dinding beton yang keras berhadapan dengan kelembutan hati yang tak kenal lelah.
Pada Sabtu pagi yang cerah itu, suasana RBMP berbeda. Kedatangan sekelompok mahasiswa dan dosen Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Santun dalam Kata, Bijak dalam Harta”.
Kegiatan ini bukan sekadar kewajiban akademik, melainkan sebuah jendela bagi calon-calon diplomat dan pembuat kebijakan masa depan untuk menyentuh langsung denyut nadi ketimpangan sosial di negeri mereka sendiri.
Mahasiwa didampingi oleh dua dosen pengampu mata kuliah, Riskey Oktavian, S.IP., M.A., dan Laurens Ikinia, BCIS.,MCS. Dalam sambutannya, Pak Riskey, menyampaikan kalimat yang menusuk: kegiatan ini adalah upaya “mengenal negara bangsa di bawah kolong jembatan.” Sebuah frasa metaforis yang mengandung kepedihan sekaligus harapan.
“Mengenal negara bangsa,” katanya, berarti anak-anak ini harus tetap mengenal cita-cita kebangsaan dan membiarkan mimpi mereka terbang setinggi langit. Sedangkan “di bawah kolong jembatan” adalah pengakuan pahit akan keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang tidak seharusnya menjadi penghalang bagi semangat belajar. Di titik inilah, retakan dalam janji “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” terlihat paling jelas dan nyata.
Anak-anak binaan RBMP, yang berusia rentang 4-12 tahun, berasal dari latar belakang keluarga yang serba kekurangan. Usia emas mereka dihabiskan di antara beton dan debu, namun cahaya dalam mata mereka tidak padam. Ketika ditanya cita-cita, jawaban mereka beragam: atlet nasional, pengusaha, guru, bahkan presiden.
Mereka adalah cucu dari para pahlawan tanpa tanda jasa—para nelayan, buruh, dan pemulung yang terus berjuang menyambung hidup di tepian Ibu Kota.
Antara Patriotisme dan Pengabaian
Dalam percakapan dengan para pengajar RBMP, terungkap masalah berlapis yang kompleks. Persoalan tidak hanya soal fasilitas belajar yang minim, tetapi juga gizi, kesehatan, tekanan psikologis akibat kemiskinan, dan ancaman putus sekolah. Apa yang dilakukan Bu Desi dan relawan adalah sebuah tindakan patriotik dalam diam. Mereka menjembatani jurang yang ditinggalkan oleh sistem.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran adik-adik mahasiswa UKI,” ujar Bu Desi sapaan akrabnya. Interaksi seperti ini bukan sekadar transfer pengetahuan praktis seperti komunikasi atau pengelolaan uang saku. Lebih dari itu, ini adalah suntikan rasa percaya diri bagi anak-anak-yang merupakan memiliki masa depan negeri ini. Mereka merasa dilihat, dianggap ada, dan diyakini bahwa mimpi mereka adalah sah.
Silaturahmi yang terjalin di bawah kolong jembatan itu menghancurkan sekat-sekat sosial. Para mahasiswa yang biasa berdebat teori-teori globalisasi dan kebijakan publik di ruang ber-AC, kini duduk lesehan, berbagi cerita dan tertawa bersama calon-calon penerus bangsa yang hidup dalam kondisi yang sangat kontras dengan teori kemajuan.
Refleksi bagi Kekuasaan dan Kelimpahan
Aktivitas PKM itu berjalan dengan sederhana: permainan edukatif, sesi bercerita, dan workshop kecil tentang mengelola uang. Namun, di setiap tawa dan sorak, tersimpan pertanyaan besar yang menggantung. Bagaimana negara hadir untuk warga seperti ini? Di mana letak tanggung jawab kolektif kita sebagai sesama anak bangsa?
Kondisi RBMP dan anak-anak asuhnya adalah cermin miniatur dari wajah Indonesia yang kerap terlupakan. Mereka bukan sekadar angka dalam statistik kemiskinan, melainkan manusia utuh dengan potensi yang bisa menyumbang pada kemajuan bangsa, jika diberi kesempatan yang setara.
Oleh karena itu, seruan dari kolong jembatan Cilincing ini patut didengar oleh semua pihak, terutama para pemangku kekuasaan. Kehadiran simbolis dari pemimpin, mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk sekadar menyapa dan menyaksikan langsung kondisi ini, bukanlah hal yang remeh. Itu akan menjadi pesan politik yang kuat: bahwa tidak ada satupun warga negara yang terlupakan, sekalipun mereka ‘tersembunyi’ di bawah kolong jembatan.
Mimpi Yang Tak Boleh Padam
Ketika matahari mulai condong ke barat dan kegiatan berakhir, anak-anak RBMP kembali ke rutinitas mereka. Para mahasiswa dan dosen pun berpamitan, membawa pulang cerita dan kesan yang jauh lebih berharga dari sekadar laporan akademik.
Rumah Belajar Merah Putih tetap berdiri, sebagai saksi bisu sekaligus pelaku aktif dari perjuangan melawan ketidakadilan melalui pendidikan. Mereka mengingatkan kita bahwa keadilan sosial bukanlah abstraksi dalam Pembukaan UUD. Ia adalah kemampuan setiap anak untuk membaca buku dengan pencahayaan yang layak, adalah keyakinan bahwa masa depan bisa dirajut meski atapnya adalah kolong jembatan.
Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan di gedung-gedung parlemen atau pusat perdagangan, tetapi juga di ruang-ruang sempit seperti ini, di mana semangat untuk maju bertarung melawan kerasnya realita. Dan di sanalah, sebenarnya, wajah asli bangsa ini diuji.